Bahagia
"Kamu jangan begitu!" Wanita itu dengan cepat mendatangiku. Wajahnya diliputi kekhawatiran.
Aku hanya diam memandangnya, bingung dengan tingkahnya.
"Kalo kamu seperti itu terus, ngeyel terus, nggak nurut, nanti kamu bisa berakhir seperti dia, loh." Dia, dengan sembunyi-sembunyi, menunjuk laki-laki yang duduk di meja kerjanya di belakangku, yang sedang dengan tekun menyelesaikan pekerjaannya.
"Memangnya kenapa dengannya?" Aku tak paham maksudnya.
"Nanti kamu diasingkan seperti dia, tak pernah dilibatkan di setiap kepanitiaan, tak pernah dapat bagian bonus, dianggap tak ada. Nanti hidupmu tak lagi bahagia."
Aku menoleh pada laki-laki yang sedang dibicarakannya aku lalu mengaitkannya dengan ingatanku.
"Masak sih dia tak bahagia?" tanyaku.
"Lah gimana mau bahagia coba kalo diasingkan seperti itu? Tak pernah diikutkan dalam setiap kegiatan begitu. Pasti kan dia tak dapat penghasilan tambahan, pendapatannya pas-pasan!"
"Bagiku, justru dia adalah orang paling bahagia di ruangan ini."
"Hah? Mana bisa?"
"Iya. Pekerjaannya paling ringan, hanya mengerjakan tugas pokok dan tak pernah terganggu dengan tugas tambahan. Apalagi tugas tambahan aneh-aneh, tak masuk akal seperti yang sering kamu kerjakan itu. Jadi tugas pokoknya terselesaikan tepat waktu." Ada raut tak terima ketika aku membandingkannya dengan laki-laki itu. "Dia selalu bisa pulang tepat waktu, jadi untuk keluarga dan sahabatnya, dia selalu punya waktu. Tidak terkungkung bekerja gila-gilaan, pulang terlambat sepertimu. Dan yang paling membuatku berpikir bahwa dia orang paling bahagia adalah kenyataan bahwa dia selalu ada waktu untuk Tuhannya, bahwa yang ditakutinya itu hanya Tuhannya, bukan manusia, bukan atasan seperti yang kamu lakukan."
Wanita itu menatapku dengan raut ambigu.
"Sekarang aku tanya padamu, benar kamu bahagia? Benarkah kamu bahagia ketika setiap detikmu dipenuhi kekhawatiran akan dimarahi atasan? Ketika di setiap waktu luangmu diisi oleh harapan bahwa tak akan ada panggilan untuk datang ke kantor dan mengerjakan tugas tambahan, yang bahkan seringnya sebenarnya adalah tugas mereka yang kemudian dibebankan padamu? Bahagiakah kamu ketika kamu hampir tak punya waktu untuk sekedar duduk tenang, menikmati hidup, dan bercengkerama dengan Tuhanmu?"
"Ah, tahu apa kamu dengan bahagia. Kan aku yang merasakannya, bukan kamu!"
Wanita itu hampir berlalu ketika aku meraih sebelah tangannya, memaksanya untuk mendengarkanku sedikit lagi.
"Itulah, kamu pun tak tahu tentang bahagiaku dan bahagianya." Aku mengarahkan pandangan pada laki-laki itu. "Jadi, sudahlah. Kita nikmati saja bahagia kita masing-masing. Iya?"
Dia melepaskan tangannya dari genggamanku lalu segera berlalu.
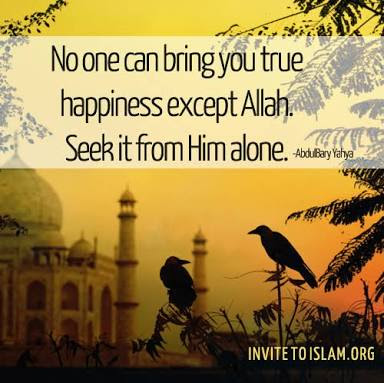



Komentar