Orang Solo Paling Tara Sopan
Setiap kali mengingat kalimat
itu, saya tertawa. Kalimat itu pernah dilontarkan oleh teman sekantor saya yang
sekaligus adalah mentor, guru, kakak, dan sahabat saya. Waktu itu kami sedang
kedatangan tamu, keluarga dari salah satu teman kantor. Saya sudah agak lupa
detail ceritanya, mengapa tiba-tiba beliau mengatakan hal itu. Yang masih saya
ingat adalah bahwa beliau dengan tertawa menunjuk kepada saya dan mengatakan,
“Dia ini orang Solo paling tara sopan sudah!”, yang artinya saya ini adalah
orang Solo paling tidak sopan. Mungkin, jika beliau mengatakan hal tersebut di depan
orang banyak, akan ada banyak sekali orang yang mengamini kata-kata beliau.
Pada dasarnya pilihan kata yang beliau gunakan itu sudah merupakan kata-kata yang
paling halus. Biasanya saya disebut dengan ‘kepala angin’, ‘pamalawang’, apa
lagi ya? Saya lupa. Sepertinya sudah terlalu banyak pilihan kata lain yang
orang gunakan untuk menilai saya yang sebenarnya artinya sama; Lancang.
Lancang. Saya sadar, saya ini
memang manusia yang sangat lancang. Maklum, walaupun berasal dari keluarga
Jawa, saya tidak pernah dibesarkan untuk menjadi bayang-bayang. Tentunya saya
mendapatkan pendidikan perilaku, tentang sopan santun, tentang cara
berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua, tentang bagaimana seharusnya
bertindak tanduk di masyarakat. Tapi orang tua saya juga mengajarkan bahwa saya
ini manusia yang punya akal, yang bisa berpikir dan bernalar. Orang tua
mengajarkan bahwa karena memiliki akal, seorang manusia itu tidak sepantasnya
hanya bisa tunduk, diam, dan menelan segala macam penderitaannya bulat-bulat.
Kata ibuk, tugasnya manusia itu memang bersabar dalam menghadapi hidup. Tapi
manusia juga memiliki kewajiban untuk ikhtiyar, untuk melakukan usaha. Ketika
merasa tertindas dan menderita, tidak seharusnya seorang manusia itu hanya diam
dan berdoa semuanya akan berubah. Perubahan itu harus diusahakan juga, tidak
hanya didoakan.
Mungkin juga saya dianggap
lancang karena saya mengatakan apa yang perlu saya katakan kepada setiap orang,
tidak peduli siapapun. Guru saya yang saya ceritakan di depan tadi sering
menyebut sifat saya ini sebagai asertif. Beliau ini juga sering menjadi korban
ke-asertif-an saya. –Maaf ya, Pak J
-. Lagi-lagi, ini adalah hasil didikan orang tua saya juga. Orang tua saya
mengajarkan bahwa rasa hormat dan penghargaan itu bukan kado gratis yang
diberikan oleh usia atau kekuasaan. Artinya, orang tidak akan serta merta
menghormati dan menghargai saya hanya karena saya dianggap lebih tua atau
berkuasa. Inilah yang membuat saya juga merasa berat sekali untuk bisa
menghormati dan menghargai orang-orang yang tidak bisa menghormati dan
menghargai orang lain. Kata ibuk, kalo ingin dihargai ya berarti harus
menghargai orang lain. Masalah itu ada untuk diselesaikan, bukan untuk
dipendam. Masalah, kekesalan, ketidaksetujuan, ketidaksamaan visi, semua itu
harus disampaikan dan diselesaikan karena jika dipendam dan disimpan hanya akan
menjadi penyakit dan ujung-ujungnya nanti bisa jadi meledak dengan hebat
seperti bom. Lebih baik disampaikan langsung daripada hanya dibicarakan di
belakang. Membicarakan di belakang itu tidak akan ada manfaatnya. Makanya saya
ini terbiasa menyampaikan apa adanya. Jika saya tidak suka, saya akan bilang
tidak suka. Jika saya tidak setuju, ya saya sampaikan saya tidak setuju. Untuk
apa memasang muka manis, mengangguk-anggukan kepala menyetujui, dan memasang
senyum lebar jika pada kenyataannya rasanya ingin menghujamkan pisau? Lebih baik
apa adanya saja, lebih tersampaikan dan bisa segera dicarikan jalan keluar.
Kata guru saya lagi, saya ini
bukan orang Jawa. Mungkin orang menganggap bahwa yang namanya orang Jawa itu
seharusnya halus, sopan, dan penurut. Ketiga hal itu, bagi sebagian orang,
mungkin tidak ditemukan pada diri saya. Padahal sebenarnya saya punya semua
itu. Hanya, lagi-lagi, kembali kepada siapa saya berhadapan. Ketika menghadapi
orang yang halus dan sopan, tentunya saya juga akan bersikap halus dan sopan.
Ketika menghadapi orang yang tidak sopan, ya bagaimana ya? Saya rasanya agak
berat untuk bisa tetap berbuat sopan. Walaupun tetap diusahakan juga
sebenarnya. Dan untuk urusan penurut, ya sama. Kembali lagi pada siapa. Saya
penurut pada orang-orang yang memang pantas diturut. Apa saya harus menurut
kepada orang yang antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan tidak
pernah sejalan? Kalopun saya memang harus menuruti orang semacam itu, apanya
yang harus saya turuti? Ucapannya atau perbuatannya? Karena saya ini hanya
satu, tidak mungkin bisa memecah diri saya menjadi dua. :D
Yah, saya rasa memang guru saya
itu benar. Saya ini memang orang Solo paling tidak sopan, suka melawan, ngeyel,
kepala angin, lancang. Tidak apa-apa saya dinilai seperti itu. Pada
kenyataannya masih banyak orang yang sayang kepada saya, yang paham bahwa saya
ini manusia yang tidak akan mungkin bisa diam jika diinjak. Itu yang penting
bagi saya. Berusaha memperbaiki diri itu pasti, seperti yang sedang saya
usahakan setiap hari. Saya sedang berusaha memperbaiki diri. Tapi memperbaiki
diri bukan berarti berusaha menjadi anak manis yang siap diikat lehernya.
Memperbaiki diri itu lebih pada berusaha menjadi manusia yang lebih baik, yang
membawa kebaikan, menjalankan tanggung jawab dan kewajiban, memberikan hak
orang lain yang dititipkan kepada saya, walaupun untuk dapat melakukan itu harus
siap dibenci beberapa orang. Asal Tuhan tidak membenci saya dan masih ada
orang-orang yang menyayangi saya, saya rasa itu sudah lebih dari cukup, kok.
Ya, saya ini orang Solo paling
tara sopan memang. ;D
 |
| Kata siapa orang Solo itu hanya bisa diam dan menjadi penurut? Wiji Thukul orang Solo.. Jokowi orang Solo.. Apa mereka selalu hanya bisa diam dan menjadi penurut? :) |
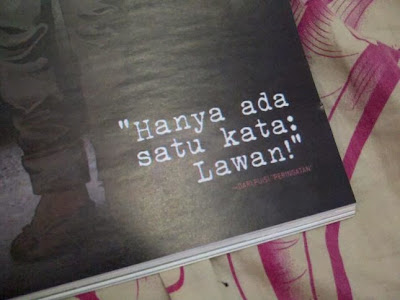



Komentar